
Di dataran tinggi Magelang, Jawa Tengah, sebuah bangunan batu berdiri megah menantang zaman. Namanya Candi Borobudur, yang bukan hanya sekadar bangunan kuno atau tujuan wisata semata, tapi sebuah narasi bisu tentang kebesaran manusia, tentang spiritualitas yang mendalam, dan tentang bagaimana sejarah bisa terbenam dalam tanah dan terlupakan.
Untuk memahami Borobudur, kita harus membaca lebih dari batu-batu yang tersusun rapi, tapi kita juga harus membaca waktu.
Borobudur dan Ambisi Kekuasaan Dinasti Syailendra

Sekitar abad ke-8 M, di lembah Kedu yang subur, Dinasti Syailendra tengah membangun kekuasaannya. Mereka bukan sekadar raja-raja biasa, melainkan pemimpin spiritual yang menganggap dirinya bagian dari jalur pencerahan. Dalam semangat inilah Borobudur lahir.
Raja Samaratungga adalah tokoh penting di balik pembangunan candi ini. Ia bukan hanya pemimpin duniawi, tapi juga pencari kebijaksanaan yang ingin meninggalkan warisan spiritual. Maka dibangunlah Borobudur — bukan di atas tanah sembarangan, tetapi di antara dua sungai suci dan dikelilingi bukit-bukit yang dianggap sakral.
Borobudur dibangun dengan konsep mandala, mewakili alam semesta dalam ajaran Buddha. Tiga tingkat utamanya yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu yang merepresentasikan perjalanan jiwa manusia dari dunia hawa nafsu menuju pencerahan mutlak.
Lebih dari 2.600 panel relief dan 500-an arca Buddha dipahat oleh tangan-tangan terampil yang tak hanya bekerja, tetapi beribadah lewat ukiran. Setiap pahatan adalah kisah — tentang kelahiran Buddha, ajarannya, dan kehidupan masyarakat Jawa kuno yang terpahat dalam batu.
Namun Borobudur bukan hanya karya spiritual. Ia juga adalah alat legitimasi kekuasaan. Dengan membangun monumen semegah itu, Dinasti Syailendra menunjukkan kepada dunia: merekalah penjaga kebijaksanaan, pemilik kekuasaan, dan penguasa spiritual tanah Jawa.
Masa Peralihan: Saat Borobudur Dilupakan
Waktu terus berjalan, dan sejarah tak pernah berhenti bergeser. Memasuki abad ke-10, kekuasaan politik di Jawa mulai mengalami transformasi. Dinasti Syailendra melemah, dan Wangsa Sanjaya — yang menganut Hindu Siwa — mulai menguat.
1. Munculnya Kerajaan Medang (Mataram Kuno)
Raja Mpu Sindok, salah satu penguasa Medang, memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada sekitar tahun 929 M. Alasannya diduga dua: tekanan dari letusan Gunung Merapi dan ketegangan politik antara penguasa Hindu dan penganut Buddha Mahayana.
Dengan perpindahan ini, wilayah dataran Kedu — tempat Borobudur berada — menjadi wilayah pinggiran yang tak lagi strategis. Pusat spiritual dan politik berpindah, dan Borobudur mulai kehilangan maknanya. Ia tidak dihancurkan, hanya perlahan ditinggalkan. Seperti rumah tua yang tak lagi dikunjungi, debu dan lumut mulai mengambil alih.
2. Era Kediri: Sastra Menguat, Borobudur Memudar
Kerajaan Kediri, yang muncul sekitar abad ke-11, menjadi pusat perkembangan budaya dan sastra Hindu-Jawa. Karya seperti "Kakawin Bharatayuddha" dan "Arjunawiwaha" menggambarkan puncak kejayaan sastra Jawa klasik.
Namun tidak ada satu pun catatan di masa Kediri yang menyebut Borobudur. Bagi masyarakat saat itu, orientasi spiritual mereka telah berubah. Candi stupa besar itu menjadi "gunung batu" yang asing di tengah sawah dan hutan.
3. Singhasari dan Sinkretisme yang Mengabaikan Masa Lalu
Raja Kertanegara dari Singhasari membawa ajaran Buddha Tantrayana dari Tibet dan Tiongkok, memadukannya dengan Siwaisme dalam bentuk sinkretisme yang unik. Meski Buddha kembali dipuja, ajarannya telah berubah. Borobudur, yang merepresentasikan Mahayana klasik, dianggap kuno dan tidak relevan.
Perhatian politik Singhasari juga beralih keluar — ke Sumatra, ke Melayu, ke luar Jawa. Borobudur tetap berdiri, tapi tanpa ritual, tanpa manusia, tanpa makna. Ia menjadi reruntuhan suci yang ditinggalkan.
4. Letusan Merapi: Alam Turut Mengubur Ingatan
Letusan demi letusan dari Gunung Merapi menyelimuti dataran Kedu dengan abu dan lahar. Borobudur terkubur secara perlahan — bukan karena kehancuran, tetapi karena pengabaian.
Tanah subur yang dihasilkan menjadikan area itu cocok untuk pertanian, dan penduduk sekitar pun hidup berdampingan dengan bukit batu besar itu tanpa tahu maknanya. Masyarakat menyebutnya hanya sebagai "gunung berundak" atau "punden berundak" dari masa leluhur.
Candi Borobudur Ditemukan Kembali oleh Bangsa Penjajah
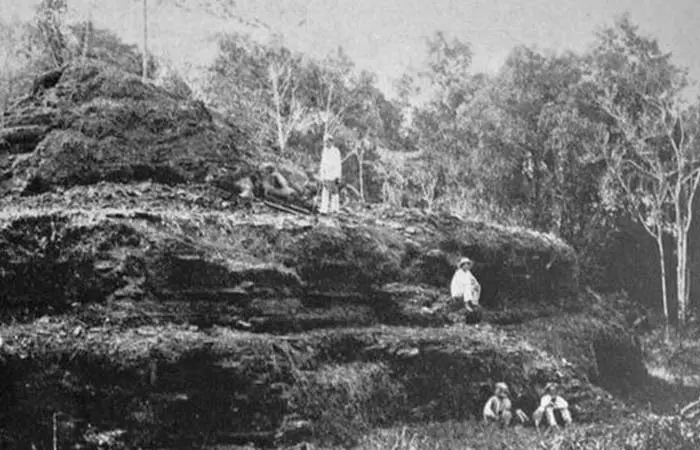
Abad ke-19, saat Tanah Jawa berada di bawah kendali kolonial, tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mendengar kabar tentang bukit misterius yang penuh pahatan di tengah hutan.
Ia mengutus insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidikinya. Setelah membersihkan semak belukar dan tanah selama dua bulan, tampaklah sebuah bangunan megah yaitu Borobudur.

Namun penemuan ini bukan berarti kebangkitan spiritual. Borobudur menjadi objek arkeologi dan eksotisme kolonial. Banyak arca dicuri, beberapa dikirim ke Belanda sebagai hadiah, dan sisanya dibiarkan terbuka tanpa perlindungan.
- Salah satu contoh paling terkenal adalah patung Buddha yang dipindahkan ke Belanda pada awal abad ke-20. Patung ini kini menjadi koleksi di Rijksmuseum, Amsterdam, dan hanya sebagian kecil dari koleksi Borobudur yang sempat dibawa ke Eropa.
- Pada tahun 1885, seorang arkeolog Belanda, H.C. Cornelius, menemukan beberapa relief yang hilang dari Borobudur dan mencatatnya dalam laporan. Namun, tidak ada upaya serius untuk melestarikan Borobudur sampai program restorasi dimulai pada tahun 1970-an.
Van Erp, seorang insinyur Belanda, memulai restorasi awal pada 1907. Tapi tanpa dana dan pemahaman penuh, upayanya terbatas. Candi ini masih rentan terhadap cuaca, pencurian, dan kerusakan.
Borobudur menjadi warisan dunia yang belum disadari pemiliknya.
Kebangkitan Nasional dan Restorasi Modern

Memasuki abad ke-20, Indonesia menuju kemerdekaan. Borobudur pun mulai dilihat kembali tapi bukan hanya sebagai situs sejarah, melainkan sebagai identitas bangsa.
Tahun 1973, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO dan negara-negara sahabat untuk memulai restorasi besar. Lebih dari satu juta batu dibongkar, diperiksa, dan disusun ulang. Butuh waktu hampir 10 tahun untuk menyelesaikannya.
Pada 1991, Borobudur diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Ia menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya bagi Buddhisme di Nusantara, tetapi juga bagi identitas sejarah Indonesia.
Borobudur Cermin untuk Masa Kini
Borobudur adalah saksi sejarah tentang bagaimana manusia membangun, melupakan, dan akhirnya kembali menghargai warisan leluhurnya. Ia bukan hanya peninggalan Buddha, tapi juga peninggalan manusia Jawa.
“Borobudur tetap berdiri. Diam, tapi penuh makna. Ia tidak pernah pergi — kita saja yang lupa.”
Kini saatnya kita tidak sekadar mengaguminya sebagai situs wisata, tapi juga memaknainya sebagai pelajaran: bahwa kejayaan bisa lenyap jika tak dijaga, dan identitas bisa hilang jika tak dikenang.